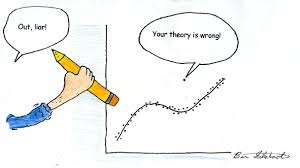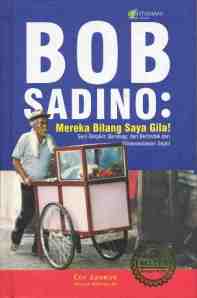Sore-sore wajah bapak saya bertekuk, karena saya harus bolak balik dapur mengurusi cumi-cumi jadi saya membiarkan saja. Namun setelah kira-kira 20 menit cumi-cumi saya matang, wajahnya masih juga cemberut saja hingga kemudian tiba-tiba saja beliau bicara “Kalau capres X yang dukung ya tukang becak!” Saya cukup kaget dan tidak paham maksudnya, saya hanya menoleh sambil menaikkan alis ke adik saya yang tengkurap di sofa, dan dia kemudian hanya menggeleng. Baiklah saya akhirnya memberanikan bertanya
“Kenapa pak? Bapak abis debat sama tukang becak masalah capres?”
Tebakan tepat sasaran
“gak juga sebenernya, tapi ya Abang itu… milih capres X”
“Terus… bapak di bantah?” saya agak menyelidik karena moodnya benar-benar terasa buruk.
“em,, ya biasalah.. tapi kan bukan level saya, saya bilang saja terkait inflasi jakarta yang turun karena capres pilihan saya, ah sudahlah…”
Adik saya tersenyum penuh arti. Bapak saya memang mendukung salah satu capres, dan saya serta adik saya sering melihat bapak saya ini sedikit berkampanye ke para tetangga yang beliau ajak bicara. Namun, kali ini tampaknya bapak saya kesal karena kampanyenya agak gagal pakai total.
Kondisi demikian tidak hanya terjadi pada bapak saya, tetapi menjadi cukup mainstream terjadi dihampir tiap individu yang memiliki suara karena kubu calon presiden kali ini benar-benar hanya terdiri dari dua, ekstrim. Apabila pilihannya hanya dua seperti ini, sebenarnya saya cukup bersyukur karena anggaran negara untuk pemilihan menjadi tidak begitu besar. Namun, yang menakutkan kemudian adalah kondisi masing-masing pendukung calon yang bisa menjadi sangat militan. Mereka akan membentuk indentitas baru yang secara tidak sadar melebur dalam satu kubu (fusion identity), mereka akan merasa sakit bila tokohnya di senggol meskipun hanya sedikit, dan menganggap individu lain yang menjadi “out group”nya dapat saja memunculkan bahaya sehingga sebelum diserang muncullah ide untuk menyerang.
Sebagai pribadi, saya bukan pendukung salah satu calon presiden, mungkin lebih tepatnya saya adalah orang yang memilih berdiri di ranah netral ketika berhadapan dengan lingkungan sosial. Mengenai pilihan saya, biarlah itu menjadi rahasia saya saja dalam hati dan bilik TPS nanti. Namun kemudian, saya juga ingin sekali ikut berkampanye, bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wapres, tetapi untuk menyuarakan kampanye atau dukungan santun atas capres-cawapres untuk masyarakat yang memiliki suara mengambang.
Sejujurnya saya mulai agak terganggu ketika akun Facebook saya, satu-satunya jejaring sosial yang sangat sering saya hidupkan, tempat dimana saya mencari hiburan, mulai juga terisi dengan kampanye (dan buruknya) dengan warnanya yang hitam. Mulai dari keturunan, agama, orang tua, label penipu, penculik, dan lain-lainnya yang membuat mata saya pedas. Yang paling akhir, tentang foto antara yang ganteng dan kurang ganteng. Hem… saya bertanya, apakah kemampuan memimpin itu berhubungan dengan gantengnya masa muda? Sungguh ajaran agama manapun tak pernah memperbolehkan seseorang untuk menghinakan fisik manusia yang telah diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan.
Sebagai rakyat jelata (karena saya belum sanggup bilang kalau saya jelita), saya memiliki harapan agar lingkungan saya dapat cerdas dan tenang dalam memilih, bukan saling menjatuhkan dan membuka aib, bukan juga dengan ngotot bahwa yang didukung adalah yang paling benar dan tidak ada cela, tidak boleh diberi pertanyaan tentang masa lalunya, atau hal-hal lain yang membuat orang seperti saya (sedikit) muak dengan militansi para pendukung yang makin hari, makin tidak sehat. Padahal di sisi lain saya juga mengakui militansi dalam politik itu diperlukan, tidak mungkinkan menjadi kader atau relawan pendukung memiliki sikap ogah-ogahan, tidak berani hidup tidak tenang serta cari aman seperti saya, tetapi kalau sudah sangat negatif… siapa yang mau menaruh simpati?
Ibaratnya, dalam menjual barang, apakah perlu sibuk menjatuhkan toko di sebarang jalan?
Saya pikir kesibukan akan lebih bermakna saat kita berusaha menampilkan dan terus menjaga kualitas sebagai bukti bahwa apa yang sedang kita jual tidak membohongi para calon pembeli.
Dan satu lagi, sepanjang saya mengenal politik (di Indonesia ini) tampaknya tak pernah ada kawan abadi, begitu juga lawan abadi.
“persaingan untuk mendapatkan kemuliaan, seharusnya dengan beradu kemuliaan. Penyanjungmu suatu saat bisa saja menjadi pemakimu. Demikian sebaliknya. Maka jangan berlebihan menyanjung atau memaki.” KH. A. Musthofa Bisri.
—-wujudkan Indonesia cerdas, dengan kampanye/dukungan santun.